
Thāriq ibn Ziyād dan Genealogi Kekuasaan Islam di al-Andalus
Sejarah Thāriq ibn Ziyād
Dalam sejarah Islam awal, penaklukan al-Andalus menandai penguatan hegemoni politik dan militer Dinasti Umayyah pada masa pemerintahan al-Walīd ibn ʿAbd al-Malik (705–715 M). Di bawah komando Thāriq ibn Ziyād, kekuatan militer Muslim berhasil memasuki wilayah Hispania yang saat itu didominasi oleh kerajaan Visigoth. Namun lebih dari sekadar keberhasilan militer, ekspedisi ini menandai awal dari kontak intens antara peradaban Islam dan dunia Latin-Kristen, dengan implikasi jangka panjang terhadap struktur politik, sosial, dan epistemik Eropa Barat.
Makalah ini menyuguhkan pembacaan ulang terhadap narasi klasik seputar penaklukan al-Andalus dengan mengedepankan pendekatan historis-kritis. Tujuannya bukan hanya untuk menelusuri kronologi dan strategi Thāriq, tetapi juga untuk memeriksa konstruksi wacana seputar identitas, otoritas, dan legitimasi dalam teks-teks historiografi Arab klasik serta interpretasi modernnya.
Dinasti Umayyah dan Strategi Ekspansionis di Barat
Sejak didirikannya pada tahun 661 M, Dinasti Umayyah telah mengarahkan kebijakan ekspansinya ke berbagai front. Di kawasan barat daya Mediterania, penguasaan atas Ifriqiya menjadi platform logistik dan militer untuk ekspedisi selanjutnya ke Hispania. Gubernur Ifriqiya, Mūsā ibn Nuṣayr, memainkan peran sentral dalam konsolidasi wilayah Berber dan penyiapan pasukan lintas laut. Penunjukan Thāriq ibn Ziyād sebagai komandan ekspedisi menunjukkan pergeseran struktur komando ke arah penguatan aktor-aktor lokal non-Arab dalam sistem Umayyah, sebuah proses yang, menurut Kennedy, mengindikasikan “bentuk rasionalisasi militer dalam struktur frontier” (Kennedy, 2007).
Etnis dan Sosial Thāriq ibn Ziyād
Thāriq berasal dari etnis Berber Afrika Utara dan memeluk Islam dalam konteks dakwah pasca-penaklukan Maghrib. Sebagai mawla Mūsā ibn Nuṣayr, ia mengilustrasikan dinamika sosial-politik di mana struktur kekuasaan Arab membuka ruang bagi partisipasi elite lokal. Ibn Khaldūn, dalam al-Muqaddimah, menekankan bahwa kelompok Berber bukan hanya sebagai subjek kekuasaan Arab, melainkan sebagai koaktor dalam proses islamisasi dan ekspansi. Dalam konteks ini, Thāriq bukan sekadar komandan lapangan, tetapi representasi dari integrasi kekuatan lokal ke dalam sistem imperium Islam.
Komposisi Pasukan dan Basis Etnis Militer
Sumber utama Ibn ʿAbd al-Ḥakam mencatat bahwa Thāriq memimpin pasukan sekitar 7.000 personel, sebagian besar dari mereka adalah mujahid Berber yang baru masuk Islam: "فخرج طارق بن زياد من طنجة في سبعة آلاف من المسلمين أكثرهم البربر" (Ibn ʿAbd al-Ḥakam, 1922: 217). Komposisi ini memperlihatkan skema tentara frontier yang mengandalkan mobilisasi lokal dengan dukungan minimal dari pusat. Sementara sebagian kecil elite Arab berfungsi sebagai perwira atau penasihat strategis, dominasi etnis Berber mencerminkan pergeseran demografis kekuatan militer Islam awal di kawasan Barat.
Strategi Operasional dan Pertempuran Guadalete
Penyeberangan Selat Gibraltar oleh Thāriq pada 711 M membuka babak baru dalam geopolitik Mediterania. Lokasi pendaratan kemudian diberi nama Jabal Ṭāriq, simbol geografis sekaligus politis dari kehadiran Islam di Eropa. Pertempuran utama terjadi di Sungai Guadalete, di mana pasukan Thāriq berhasil mengalahkan Raja Roderik dari Visigoth. Meskipun beberapa elemen dramatik—seperti pidato pembakaran kapal—kemungkinan merupakan konstruksi literer posterior, mereka tetap memiliki nilai simbolik dalam membangun narasi heroik Islam.
Studi komparatif antara narasi Islam dan kronik Latin menunjukkan adanya distorsi mutual dalam penilaian terhadap jumlah pasukan, sebab-musabab konflik, dan dampak jangka panjang. Namun demikian, konsensus historiografis menyetujui bahwa operasi Thāriq merupakan manuver militer yang terencana dan berisiko tinggi yang berhasil karena koordinasi logistik, pengetahuan medan, dan keretakan internal di pihak Visigoth.
Administrasi Awal al-Andalus dan Ketegangan Intra-Elite
Pasca-kemenangan, Thāriq mengonsolidasikan otoritas Islam di kota-kota besar seperti Toledo dan Córdoba. Reformasi administratif meliputi rekonstruksi pajak berbasis jizya dan kharaj, serta integrasi elite lokal ke dalam sistem dhimmah. Namun hubungan Thāriq dengan Mūsā ibn Nuṣayr memburuk, terutama terkait distribusi hasil rampasan dan otoritas teritorial. Kedua tokoh tersebut akhirnya dipanggil ke Damaskus, mencerminkan intervensi kekuasaan pusat dalam mengatur ulang hierarki kekuasaan di pinggiran imperium.
Ketiadaan catatan historis tentang Thāriq pasca-kepulangannya ke Damaskus menjadi bahan spekulasi di kalangan sejarawan. Namun dalam memori kolektif Islam, ia tetap dikenang sebagai pelopor utama masuknya Islam ke Eropa.
Kritik Sumber dan Historiografi
Sumber-sumber primer seperti karya Ibn ʿAbd al-Ḥakam dan al-Maqqarī, meskipun kaya naratif, ditulis jauh setelah peristiwa. Mereka lebih mencerminkan dinamika memori kolektif daripada kronik kontemporer. Oleh sebab itu, penting untuk membaca sumber-sumber ini melalui pendekatan hermeneutik dan kontekstual.
Historiografi modern, sebagaimana dianalisis oleh Collins (1989) dan Kennedy (2007), cenderung mengadopsi metode triangulasi antara sumber Arab dan Latin. Ketegangan epistemik antara “sejarah sebagai fakta” dan “sejarah sebagai konstruksi” terlihat jelas dalam narasi tentang Thāriq, terutama dalam aspek mitologisasi dan etnonasionalisme.
Warisan dan Signifikansi Peradaban
Ekspedisi Thāriq tidak hanya membuka wilayah baru bagi imperium Islam, tetapi juga menciptakan ekosistem kultural dan ilmiah yang akan berkembang dalam bentuk al-Andalus. Institusi pendidikan, filsafat, arsitektur, dan interaksi antaragama yang muncul di wilayah ini menjadi titik awal bagi transformasi peradaban Eropa.
Dengan menamai Gibraltar sebagai Jabal Ṭāriq, warisan Thāriq tertanam dalam toponimi geopolitik modern. Dalam narasi Islam kontemporer, ia diangkat sebagai paradigma keberanian, visi strategis, dan integritas moral.
Kesimpulan
Thāriq ibn Ziyād merupakan figur sentral dalam narasi penaklukan Islam awal yang tidak hanya berhasil dalam dimensi militer, tetapi juga menandai transisi besar dalam sejarah kultural Mediterania. Kepemimpinannya mencerminkan kompleksitas identitas dalam kekuasaan Islam: integrasi antara Arab dan non-Arab, pusat dan periferi, serta memori dan sejarah.
Studi terhadap Thāriq mengharuskan pembacaan lintas sumber dan pendekatan kritis terhadap konstruksi historiografis. Dalam konteks ini, penaklukan al-Andalus menjadi lebih dari sekadar ekspansi militer; ia adalah refleksi dari dinamika transhistoris yang membentuk wajah Islam global dan Eropa modern.
4 Komentar
Thāriq ibn Ziyād dan Genealogi Kekuasaan Islam di al-Andalus <a href="http://www.gvhjkya14m1z34863lme3n7i56y295u8s.org/">alzqcesnct</a> [url=http://www.gvhjkya14m1z34863lme3n7i56y295u8s.org/]ulzqcesnct[/url] lzqcesnct http://www.gvhjkya14m1z34863lme3n7i56y295u8s.org/
lzqcesnct Guest
06 Nov 2025

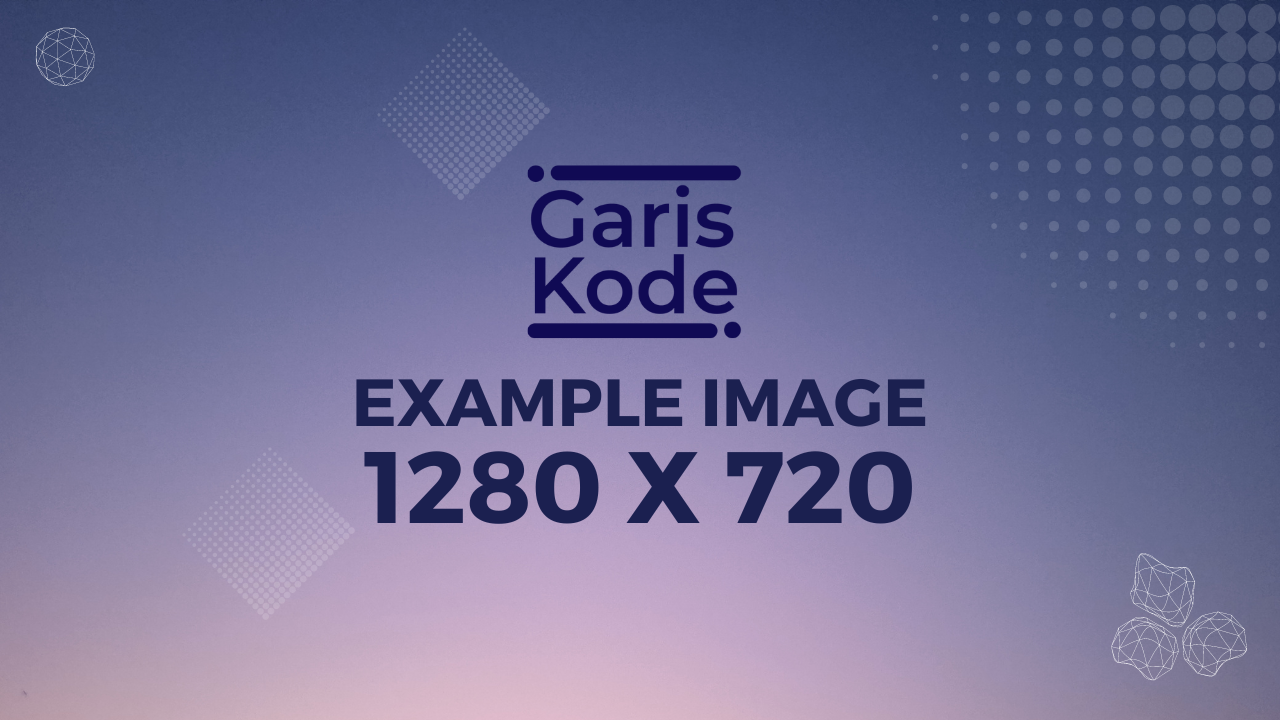

79230r
* * * <a href="http://dmclog.com/index.php?zukecl">Win Free Cash Instantly</a> * * * hs=138f9da9d9284754e7ddb8e48f481477* ххх* Guest
30 Jul 2025